Ada Apa dengan (Bangsa) Kita?
Saya bicara tentang topik berat seperti politik dan kebangsaan itu... Rasanya seperti bukan saya! Pertama karena merasa bukan kapasitasnya. Ke dua, lebih pada keyakinan bahwa ideologi politik Kita bisa jadi tidak sejalan dengan orang lain yang saya kasihi, dan ketika bicara politik, Kita bisa jadi mudah tersulut dengan kondisi dan keyakinan Kita yang (lagi-lagi: bisa jadi dideskriditkan orang lain yang tidak sejalan) dan berujung jadi debat kusir berkepanjangan.
I'm not gonna talking about politics! Apa yang saya akan tuliskan kemudian lebih pada pandangan saya mengenai keadaan yang menjadi jamur karena dipolitisir.
Ini adalah pandangan saya mengenai sikap tak senonoh tapi tak pernah dianggap terlalu serius di belahan dunia mana pun bernama RASIS.
Indonesia gempar dengan banyak hal bersifat rasis, terutama bila ada sangkut pautnya dengan politik. Mendadak semua orang merasa pandai berpolitik, tapi sering lupa bahwa topik politik seharusnya bersinggungan dengan norma dan budaya (baca: tata krama) dan TIDAK bersangkutan dengan warna kulit atau agama yang dianut.
Semua warga negara Indonesia berhak berpolitik, menjalankan agenda politik, berpartisipasi dalam politik, termasuk menjadi objek politik. Warga negara Indonesia di sini tidak dicantumkan dengan aneka tanda harus berwarna kulit tertentu, lebar mata tertentu, apalagi agama tertentu.
Jadi para petinggi negara yang terhormat... Dengan segala hormat... Saya memohon, jangan jadi contoh yang buruk bagi anak-anak kita. Banyak orangtua mengira, ditemani anak menonton video rapat mediasi petinggi DKI Jakarta adalah acara yang aman dan mendidik. Tanpa mereka sadar ketika seorang peserta rapat berteriak "Dasar C**a an***g!!"
Atau ketika membuka sosial media, tak ada angin tak ada hujan, Anda sebagai orangtua menekan tombol 'LIKE' mengenai berita berbau serupa yang di-share via sosial media, dan tentu saja otomatis tampil di wall putera/puteri cilik kita. Lalu ia tak sengaja penasaran dengan berita yang di-like ayahnya, kemudian membaca komentar para netizen yang umumnya bernada lebih tajam dari beritanya...
Saya kehabisan kata.
Saya akan kembali pada janji saya untuk tidak membahas politik dalam konteks ini... Maka saya hanya akan ceritakan pandangan saya pribadi mengenai rasisme.
Indonesia yang katanya begitu heterogen melahirkan anak-anak yang jauh lebih heterogen. Ada anak keturunan Jawa-Batak, Sunda-Padang, Makassar-Ambon, dan lain-lain. Malah tak jarang sekarang makin heterogen karena ada sisipan tambahan. Jawa-Batak-Jerman, Sunda-Arab-Betawi, Belitung-Cina-Palembang, dan lain-lain. Indahnya luar biasa hasil perkawinan antar ras itu!
Kala saya kecil, saya mengalami aneka vase berbudaya. Masa cilik di Pematang Siantar (kota kecil di Sumatera Utara, perkebunan kelapa sawit), teman saya mayoritas adalah orang Batak dan agama mayoritasnya adalah Kristen Protestan. Sulit sekali memberitahu bahwa nama saya Ike, dengan huruf "e" dibaca dengan rahang tertutup, bukan "e" yang menarik bibir ke belakang. Sementara saya... Khas dengan logat Jawa saya. Lalu sementara saya bicara dengan suara yang halus, cenderung pelan... Teman-teman saya secara alami memiliki nada suara yang tinggi dan keras. But then, I have no problem with them. Walaupun saya sempat menangis keras di pasar karena ketakutan, seolah semua pedagang sedang saling amuk, padahal ya memang itu cara bicara mereka. Selanjutnya saya malah sangat kagum dengan keterusterangan dan apa adanya teman-teman bersuku Batak itu.
Saya dan beberapa teman beragama Islam adalah golongan minoritas di sana. Kami lah yang dipindahkan ke kelas lain saat pelajaran agama. Tapi semua tidak mengubah keadaan apapun.
Ketika menginjak kelas 5 SD saya pindah ke Surabaya. Alih-alih senang karena pulang ke kampung, saya justru lebih banyak mengeluh. Berbeda dengan orang Batak yang berwajah kotak cenderung terlihat garang, tapi terbuka... Orang Jawa Timur di sekolah saya dulu mayoritas adalah keturunan Tionghoa-Surabaya. Tidak banyak bicara, berwajah dingin, dan tidak selalu menampakkan antusiasme berlebih seperti teman-teman saya sebelumnya.
Tapi lebih dari teman-teman saya yang tulen Jawa seperti saya, teman-teman saya yang berketurunan Cina-Surabaya ini adalah orang-orang yang ulet dan ringan tangan. Bila sudah cukup mengenal, mereka juga ternyata cukup bersahabat dan apa adanya. Tapi tiada kata sifat yang lebih tepat dari "ulet" dan "pekerja keras" untuk menggambarkan karakter mereka di dalam ingatan saya.
Setelah itu, kehidupan saya jauh lebih mudah dalam hal bersosialisasi. Di Jakarta saya bertemu dengan banyak orang dari berbagai keturunan dan asal. Di sana juga saya bertemu dengan orang-orang keturunan Kalimantan, hingga yang berdarah Arab, Amerika, dan lain-lain.
Di lingkungan kerja saya juga melihat aneka kenyataan lain yang pada akhirnya menjelaskan kenapa orang-orang keturunan Tionghoa itu kaya. Atau berhasil dalam pekerjaannya.
Ini semua bukan karena gen, bukan darah, tapi lebih pada pendidikan yang mereka anut tanpa melupakan akar budaya mereka.
Seperti sudah saya ceritakan, mayoritas warga keturunan Tionghoa tidak selalu kaya dari sono- nya. Ayah, ibunya bisa jadi hanya penjual mie ayam, tapi bisa menyekolahkan ketiga anaknya ke perguruan swasta bergengsi di Jakarta. Kadang mereka hanya bersendal jepit dan celana pendek ketika main ke pusat perbelanjaan bonafit, tapi di parkiran ternyata mobilnya high-end built-up berharga milyaran rupiah.
Apakah mereka korupsi? Apakah mereka memakan uang orang lain? Apakah mereka menipu? Apakah mereka menggunakan cara jahat untuk memperoleh keuntungan?
Orang keturunan Tionghoa dalam sepengetahuan saya kaya karena mereka ulet, mereka penghitung kemungkinan yang baik, mereka ketat sekaligus tertib dengan uang, mereka strik dengan batasan modal dan keuntungan, mereka penuh perhitungan, mereka juga mempunyain impian yang realistis dan terstruktur, dan mereka memiliki jaringan yang kuat.
Lalu ketika mereka kaya... Apakah kita harus marah dan menghina mereka? Apakah kita sudah cukup berusaha? Apakah kita sudah cukup bekerja keras dan berhemat?
Lalu agama... Indonesia bukan negara berbasis agama. Karenanya Pancasila kita berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa," bukan menyebut salah satu Tuhan dalam aneka agama yang diakui di Indonesia.
Saya ingat sekali dengan kepala sekolah sebuah SD di Jakarta Timur yang berkata, bahwa Islam adalah agama rahmatan lil'alamin. Dengan kebaikan sikap, budi, dan pikiran umat Islam pasti bisa membawa umat lain kembali ke jalan Allah, SWT.
Singkat saja, pikiran saya langsung terlontar ke seorang sahabat di masa SD di Jakarta. Ia kerap di-bully karena non-muslim dan dikatai pemakan babi, dan aneka predikat lainnya. Pikiran saya juga langsung teringat kepada masa SD di Pematang Siantar, saya lah yang minoritas dan saya lah satu dari sedikit yang tidak mengkunsumsi daging babi. Tapi saya tidak pernah dibully karena ke Islaman dan keyakinan saya.
Saya selalu tak pernah menghiraukan predikat yang diberikan teman saya pada teman non-muslim ini. Buat saya, dia adalah refleksi saya di Pematang Siantar, dalam kedaan yang lebih pelik. Menjadi minoritas saja susah, apalagi dibully pula! Kami selalu pergi dan pulang sekolah bersama, karena kami bertetangga. Dan seandainya saja ada yang tahu... Bila saya main ke rumahnya, ia tak pernah menyuguhi saya minuman dari dalam rumah, dan justru membelikan minuman ringan di warung. Begitu besar rasa hormat dan penghargaannya pada keIslaman saya, padahal saya sendiri juga dulu tidak terlalu memperdulikan hal itu.
Saya dulu sempat berfikir, para pembully itu seharusnya malu dengan sikap teman saya ini. Inilah sikap toleransi yang elegan dan penuh pengertian.
Saya ingin berkaca pada sikap Rasulullah, SAW dan cara beliau memperlakukan kaum Yahudi di masanya. Dan menjadikan sikap Beliau sebagai tauladan dan menyesuaikannya dalam masa ini.
Indonesia adalah negara yang luar biasa indah, karena warnanya, karena perbedaan, dan karena selama ini kita hidup sebagai bangsa yang menganut toleransi yang tinggi.
Lalu kenapa sekarang berubah?
Karena media? Karena dipolitisir? Karena sosial media? Karena teman? Karena apa?!
Apapun alasannya, semua kan kembali pada diri kita sendiri. Pada toleransi dan kemanusiaan kita.
Sekali lagi mengutip ucapan pak kepala sekolah, karena kebenaran itu bisa jadi sangat relatif dan bisa jadi sangat universal.
#celoteh galau seorang warga negara yang menolak diprovokasi dengan hal-hal relatif itu.
Sumber foto: http://m.merdeka.com/sehat/korban-rasisme-cenderung-lebih-mudah-gemuk.html

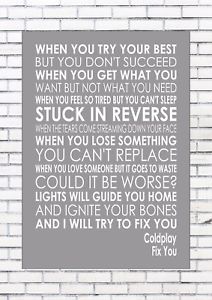

Komentar
Posting Komentar